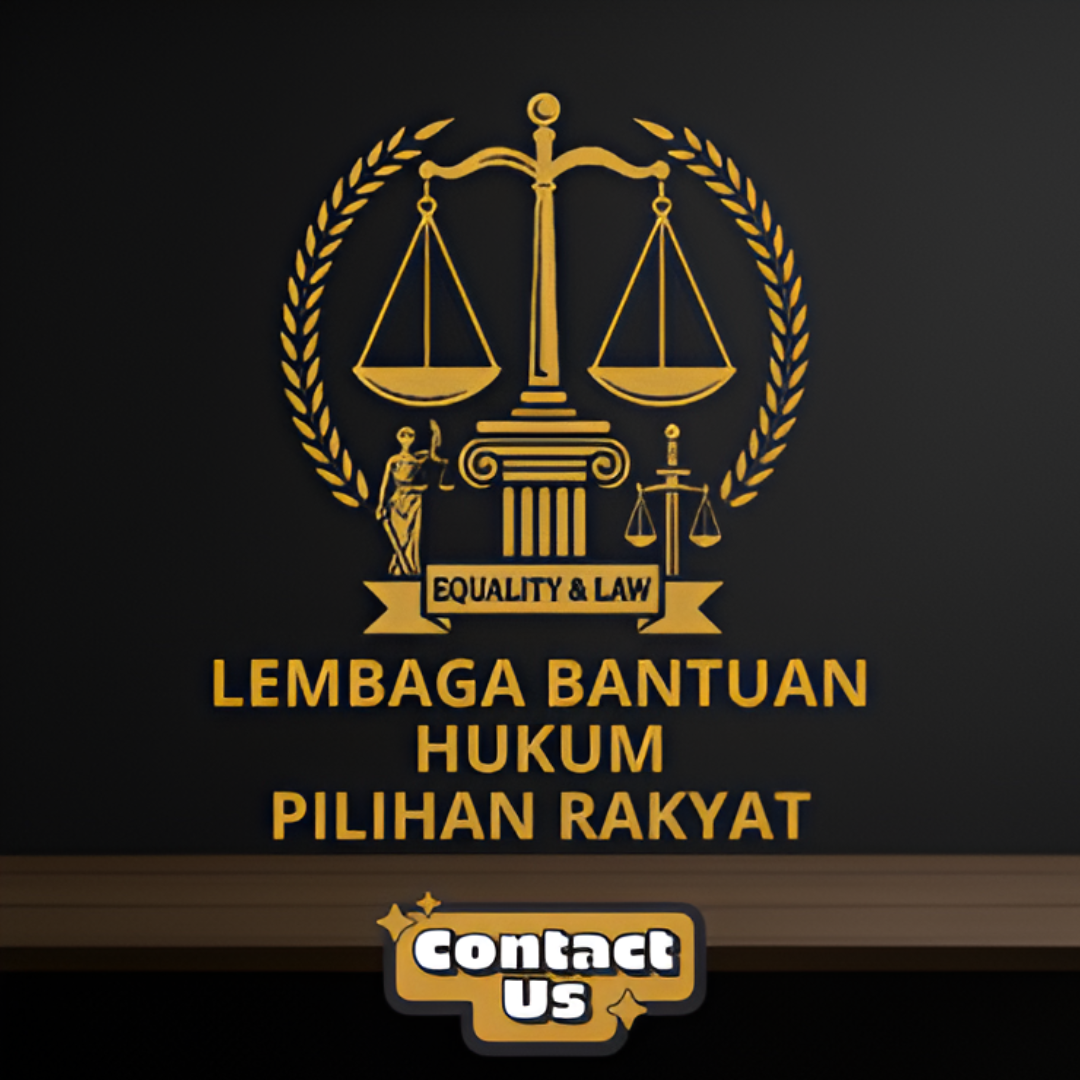Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Mata dunia seketika tertuju ke Indonesia ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menarik sejumlah kontainer frozen shrimp asal Indonesia. Alasannya bukan sekadar administratif, melainkan karena indikasi keberadaan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di dalam produk tersebut. Kasus ini sontak mengguncang industri perikanan nasional. Ia bukan hanya perkara mutu pangan, melainkan juga ujian terhadap integritas sistem pengawasan negara, tanggung jawab lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di pasar global.
Cs-137 bukanlah unsur yang muncul secara alami. Ia merupakan hasil dari fisi nuklir produk limbah dari aktivitas reaktor atau sumber radioaktif industri dan medis. Dalam jumlah kecil sekalipun, Cs-137 berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Zat ini bersifat bioaccumulative, artinya dapat menumpuk dalam tubuh makhluk hidup dari waktu ke waktu. Risiko yang menyertai paparan jangka panjang meliputi gangguan jaringan, penurunan fungsi organ, hingga peningkatan risiko kanker.
Menariknya, kadar Cs-137 yang ditemukan dalam udang beku asal Indonesia sekitar 68,48 Bq/kg ± 8,25 Bq/kg sebenarnya jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA, yaitu 1.200 Bq/kg. Namun, di balik angka “aman” itu tersimpan pertanyaan besar: jika radiasi ini tidak membahayakan, mengapa negara tujuan impor bereaksi keras? Jawabannya sederhana namun getir: karena kontaminasi radioaktif bukan sekadar soal kadar, melainkan soal ketidakpastian sumber dan kelemahan sistem pengawasan.
Investigasi gabungan Bapeten, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup menemukan bahwa sumber radiasi tidak berasal dari tambak atau kawasan hulu. Jejaknya justru tercium di sekitar pabrik pengolahan udang PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) di kawasan industri Cikande, Banten. Dugaan mengarah pada aktivitas industri logam di sekitar lokasi terutama dari tempat peleburan besi bekas yang kemungkinan besar mengandung residu radioaktif. Artinya, kontaminasi itu bisa jadi bukan berasal dari laut, melainkan dari udara dan debu logam yang menyusup ke lingkungan produksi.
Namun di balik pernyataan resmi yang tampak menenangkan, muncul serangkaian pertanyaan kritis yang belum dijawab tuntas. Seberapa jauh sebenarnya penyebaran radiasi di area sekitar pabrik? Apakah warga, petambak, dan pekerja di radius beberapa kilometer sudah menjalani pemeriksaan medis atau pemantauan paparan lingkungan? Laporan publik tidak menjelaskan sejauh itu. Yang muncul di ruang media justru narasi bahwa “situasi terkendali” kalimat yang terlalu sering digunakan ketika data sebenarnya masih gelap.
Sumber Cs-137 juga belum jelas benar. Jika benar berasal dari bahan logam impor yang sudah terkontaminasi, berarti ada kegagalan di tingkat pengawasan impor material berisiko tinggi. Namun jika berasal dari aktivitas lokal, maka yang dipertanyakan adalah efektivitas regulasi industri logam yang kerap menutup mata terhadap praktik daur ulang bahan berbahaya tanpa pemantauan radiasi. Dalam kedua kemungkinan itu, yang disorot tetap satu: lemahnya kontrol negara terhadap bahaya yang tidak kasatmata.
Dampak ekonomi dan reputasi tidak kalah berat. Industri udang merupakan salah satu penyumbang devisa ekspor terbesar Indonesia. Sekali kepercayaan buyer luar negeri goyah, pemulihannya bisa bertahun-tahun. Bayangkan, satu kasus saja mampu mencoreng seluruh rantai pasok yang melibatkan ribuan nelayan dan pekerja tambak. Para eksportir pun kini harus menanggung biaya tambahan untuk pengujian radiasi, sertifikasi ulang, hingga audit lingkungan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif negara, bukan beban pelaku usaha semata.
Kasus ini membuka luka yang lebih dalam: kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan pangan dan pengawasan lingkungan. Ketika pengawasan impor longgar, ketika kawasan industri berdiri tanpa audit radiasi, dan ketika komunikasi risiko dilakukan secara tertutup, maka publik sebenarnya sedang dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan. Transparansi menjadi barang langka, sementara kepercayaan publik kian tergerus. Padahal, dalam era keterbukaan, kejujuran data jauh lebih menenangkan daripada klaim “semua aman” yang tanpa bukti.
Indonesia memang tidak memiliki reaktor nuklir aktif, tapi bukan berarti bebas dari risiko radiasi. Limbah industri, alat medis bekas, hingga material logam impor bisa menjadi pintu masuk kontaminasi nuklir yang sulit dilacak. Celah inilah yang seharusnya ditutup dengan kebijakan preventif, bukan sekadar langkah reaktif setelah krisis muncul di halaman depan media internasional.
Kasus udang Cs-137 seharusnya menjadi pelajaran pahit bahwa keamanan pangan bukan sekadar urusan laboratorium, melainkan cermin integritas negara. Jika sistem pengawasan kita tetap bergantung pada keberuntungan, maka suatu hari kontaminasi yang lebih berbahaya bisa menyentuh meja makan tanpa kita sadari. Dan ketika itu terjadi, yang rusak bukan hanya produk, melainkan kepercayaan dunia terhadap nama Indonesia.